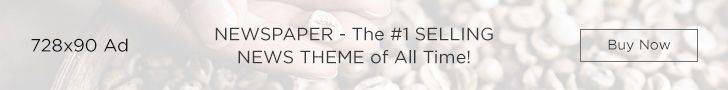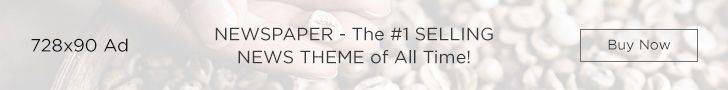
Sironline.id, Jakarta – Pemerintah bersama DPR berencana akan mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dalam waktu dekat. Namun banyak kalangan masyarakat sipil menolak, salah satunya dimasukkannya hukum hidup di masyarakat atau living law ke dalam RKUHP tersebut. Pemerintah dan DPR menyepakati akan melakukan pembahasan akhir rumusan RKUHP pada 29-30 Agustus 2019 dan siap mengesahkannya pada September 2019.
Dosen hukum pidana Universitas Bina Nusantara, Ahmad Sofian, mengatakan hukum yang hidup di masyarakat tidak perlu dijadikan hukum yang tertulis. Pasalnya, hukum tersebut mengalami evolusi seiring dengan kearifan lokal. “Pelanggaran atas hukum yang hidup, hanya bisa dituntut di dalam masyarakat yang masih mengakuinya sebagai norma,” katanya dalam diskusi bertema ‘Living Law dalam RKUHP’ di kantor YLBHI, Jakarta, Senin (26/08/2019).
Lebih lanjut Ahmad Sofian mengatakan bahwa untuk tindak pidana adat yang sudah menjadi bagian norma hukum yang bisa diberlakukan secara nasional maka dapat dirumuskan sebagai norma dalam RKUHP. Ia menambahkan bahwa hukum pidana adat itu terdiri dari heterogen antar suku, umumnya tidak tertulis, suasana kebatinan, tanggungjawab komunal dan sanksi adat tidak mengenal formil dan materil. “Pidana formil ini yang merepotkan. Hukum adat tidak memberikan batasan mana administrasi,” tuturnya.
Senada dengan Sofian, Dominikus Rato Akademisi Universitas Jember menambahkan bahwa Indonesia ini budaya tutur bukan budaya tulis. Ketika budaya tutur diformalkan pada budaya tulis, kata dia, akan terjadi goncangan karena bertentangan dengam filosofi RKUHP. “Hukum adat tidak ada pembidangan. Ketika manunggal dipecah-pecah akan terjadi kesakitan ini membuat ruang disintegrasi,” kata Dominikus. Karena itu Dominikus meminta biarkan negara membuat hukum negara. Jangan turut campur dengan hukum adat. Apabila ada kasus hukum adat, maka selesaikan terlebih dahulu melalui hukum adat. “Berikan hak yang untuk hukum adat,” ujarnya.
Wakil Ketua Advokasi YLBHI, Era Purnama Sari mengatakan masuknya living law seperti hukum adat dalam RKUHP akan berpotensi mengkriminalisasi masyarakat. Menurut Era, potensi tersebut dapat terjadi jika tafsir tersebut diserahkan kepada aparat penegak hukum. Apalagi, living law yang dalam masyarakat Indonesia sangat banyak. Karena itu, akan sulit menentukan living law mana yang akan digunakan pijakan bagi penerapan pidana. “Bagaimana negara akan menentukan menurut hukum adat yang mana pelanggarannya. Karena indikatornya masing-masing berbeda-beda. Ini berbahaya lagi. Kalau betul bahwa hukum yang di dalam masyarakat tidak ditafsirkan sebatas hukum adat, maka ini penyalahgunaan atau kriminalisasi itu berbahaya,” jelasnya.
Era menambahkan living law atau hukum adat di masyarakat sangat dinamis dan fleksibel. Sehingga, hukum adat akan mati jika diletakkan dalam RKUHP yang kaku. Rumusan living law tercantum dalam RKUHP Pasal 2 ayat 1 dan 2. Adapun bunyi Pasal 2 ayat 1, yaitu “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-undang ini.”
Sedangkan Pasal 2 ayat 2 berbunyi, “Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.”
Sementara itu, Aktivis Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tommy Indyan mengatakan negara memang mengakui keberadaan masyarakat adat dan hukum adat. Hal tersebut antara lain dapat dilihat di Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Desa dan sejumlah peraturan menteri. Namun, pengakuan tersebut kerap tumpang tindih dengan aturan hukum satu sama lain. “Semisal soal, kalau ada sengketa atau pidana atau apapun soal tanah misalkan yang berakibat pada pidana. Hakimnya nanya, kamu punya bukti atas tanah itu? yang ditanya sertifikat. Katanya hukum tidak tertulis (adat), kalau tidak tertulis ya tidak ada sertifikat. Yang ada adalah catatan-catatan adat yang memastikan catatan adat itu masih ada,” jelas Tommy.
Tommy mengusulkan agar pemerintah dan DPR membuat undang-undang tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat sebagai satu kesatuan masyarakat adat, sekaligus mengatasi tumpang tindih. Undang-undang tersebut mencakup masyarakat adat, wilayah adat, hutan adat, tanah adat dan hukum adat.
Guru Besar Antropologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Sulistyowati Irianto menambahkan pencantuman hukum yang hidup atau adat dalam negara bisa melegalisasi politisasi identitas. Semisal yang tercantum dalam peraturan daerah-peraturan daerah yang diskriminatif terhadap perempuan. Aturan yang diskriminatif terhadap perempuan ini juga ditemui dalam RKUHP yang memperluas pasal zina. “Perempuan termasuk warga adat, kelompok miskin sering mengalami politisasi identitas karena seksualitasnya, atau agama atau kepercayaan atau etnisitas atau ras. Indonesia banyak contoh kasus-kasusnya,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, anggota Panitia Kerja RKUHP DPR RI, Arsul Sani mengatakan tidak akan menghilangkan living law dalam RKUHP. Menurutnya, pasal tersebut untuk menghormati living law atau hukum adat yang sudah ada di Indonesia. “Kita ini hidup di negara dimana sistem hukumnya tidak tunggal. Ada sistem hukum barat yang kita warisi dari penjajah Belanda, ada sistem hukum Islam, dan ada juga sistem hukum adat yang tidak tertulis. Nah living law yang ada di KUHP ini ditujukan untuk menghormati hukum adat yang pada kenyataan ada di negara kita,” jelas Arsul Sani.
Arsul Sani menjelaskan setidaknya ada 2 pilihan bentuk living law yang masih menjadi pembahasan DPR dan pemerintah. Keduanya yaitu peraturan daerah dan kompilasi hukum adat yang akan berlaku di daerah masing-masing. Ia menegaskan pencantuman living law ini tidak menakutkan dan akan mengkriminalisasi masyarakat adat seperti yang dibayangkan sejumlah LSM dan akademisi. (D. Ramdani)